KONVERSI MINYAK TANAH KE GAS ELPIJI
Pertengahan tahun 2007 pemerintah membuat kebijakan untuk mengkonversi minak tanah ke gas elpiji dengan alasan untuk mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya mencapai 30 triliun. Selain itu, alasan lain diberlakukannya konversi tersebut karena penggunaan gas elpiji lebih ramah lingkungan daripada minyak tanah. Memang pada dasarnya konversi tersebut memiliki efek yang bagus, tetapi dalam penerapan kebijakannya pemerintah melakukan sejumlah kesalahan mendasar yang menimbulkan masalah masyarakat.
Sejak awal, pemerintah memang sudah tidak konsisten dengan keputusannya. Hal ini terbukti dengan dibatalkannya gagasan konversi minyak tanah ke batu bara pada tahun 2006 oleh Wapres Jusuf Kalla, tentu saja ini membuat kecewa masyarakat yang sudah mulai bersiap-siap mengganti minyak tanah ke batu baru. Dan juga mengecewakan para perajin tungku batu bara dan para peneliti yang telah berhasil membuat tungku batu bara modern, yang bisa mengatur nyala api dan menghemat pemakaian batu bara. Di sejumlah pameran, misalnya, kreativitas masyarakat membuat tungku batu bara sudah mulai bermunculan guna menyambut era konversi minyak tanah ke batu bara itu. Beberapa peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan perguruan tinggi, seperti di Universitas Sriwijaya, Palembang, telah berhasil membuat alat sederhana untuk mencairkan batu bara. Batu bara cair ini harganya lebih murah daripada minyak tanah dan sangat mudah pemakaiannya, sama seperti pemakaian minyak tanah. Baiknya lagi, semua jenis batu bara--baik yang muda (kadar karbonnya rendah) maupun yang tua (kadar karbon tinggi), bisa dicairkan. Dan batu cair ini ternyata tidak hanya bisa dipakai sebagai pengganti minyak tanah, tapi juga pengganti solar. Bahkan dengan sedikit treatment kimia, batu bara cair pun bisa diubah jadi premium.
KOnversi minyak tanah ke gas elpiji memang menimbulkan banyak pro dan kontra. Selain alasan di atas, pemerintah terkesan sangat tidak siap dengan kebijakan mengkonversi minyak tanah ke gas karena tidak memikirkan beberapa aspek yang ada di masyarakat. Misalnya dari segi aspek fisik, minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya mudah, pengemasannya mudah, dan penjualan sistem eceran pun mudah. Masyarakat kecil, misalnya, bisa membeli minyak tanah hanya 0,5 liter (katakanlah Rp 1.500 dengan harga subsidi) dan mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 0,5 liter bisa juga dimasukkan ke plastik. Kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian elpiji. Ini karena elpiji dijual per tabung, yang isinya 3 kg, dengan harga Rp 14.500-15.000. Masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli elpiji hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding minyak tanah. Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia (minyak tanah dan elpiji) tersebut, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Kondisi ini tampaknya belum diperhatikan pemerintah. Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan, karena penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan terkadang kurang. Ini berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran, satu atau bahkan setengah liter sekalipun. Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji akan menimbulkan masalah seperti yang disebutkan di atas.
Dengan demikian, mestinya kebijakan konversi gas tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi secara komprehensif. Dalam kaitan ini, kondisi masyarakat dan peta sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan mestinya dikaji terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji.
Noveradika Priananta
Ilmu Komunikasi / 153030037
Selasa, 16 September 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

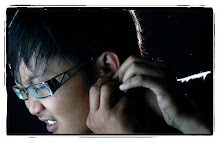
Tidak ada komentar:
Posting Komentar